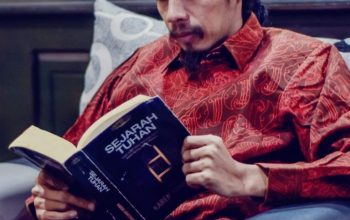Oleh Rausi samorano
Forumkota.com Ada yang bergetar dalam denyut republik ini. Ia bukan sekadar riak protes, melainkan tanda bahaya : alarm keras bagi Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa pekan terakhir, publik dipaksa menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan negara justru semakin jauh dari keberpihakan pada rakyat kecil. Subsidi dikurangi, harga-harga merangkak naik, sementara bahasa para pejabat negara yang terdengar di ruang publik lebih sering bernada menggurui, bahkan bullying. Alih-alih simpati, yang hadir justru arogansi.
Ironisnya, di tengah situasi sulit rakyat, negara justru memilih jalan lama: membungkam kritik dengan tangan besi. Aparat bergerak represif, aksi protes dihadang, dan suara yang berbeda diseret ke ruang sunyi. Semua ini bukan sekadar gejala sehari dua hari, melainkan cermin dari pola kekuasaan yang makin mirip wajah lama yaitu Orde Baru.
Kekhawatiran itu bukanlah kabar baru. Sejak Prabowo pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, para pegiat demokrasi, pengamat politik, bahkan sebagian intelektual publik, telah menaruh tanda tanya besar “apakah figur yang ditempa dalam kultur kekuasaan Orde Baru mampu memimpin demokrasi tanpa terjebak pada bayangannya sendiri?” Pertanyaan itu kini menemukan jawabannya. Pola-pola lama mulai muncul. Dan sejarah mengajarkan, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar mati.
Retorika “demi rakyat” yang kerap berkobar di podium presiden terdengar nyaring, tapi justru semakin kosong ketika di lapangan rakyat berhadapan dengan aparat yang represif. Apologi demi apologi tak cukup untuk menutupi luka lama. Ingatan kolektif bangsa ini masih menyimpan trauma panjang: wajah Soeharto dengan senyum paternal, tangan kanan yang mengulurkan “kasih”, dan tangan kiri yang menggenggam senjata. Simbol ganda itulah yang kini kembali hadir dalam bayang masyarakat setiap kali melihat tindakan represif negara.
Tewasnya seorang demonstran, Affan Ojol menambah bara di tengah kekecewaan. Ia bisa saja menjadi simbol perlawanan, sebagaimana sejarah selalu mengabadikan korban sebagai martir. Dari Trisakti hingga Semanggi, dari reformasi hingga gelombang protes di era pasca-Soeharto, kita tahu satu hal, kematian akibat represi negara tak pernah berhenti di liang kubur. Ia menjelma api yang bisa menjalar ke jalan-jalan, menyalakan gerakan, dan mengguncang kekuasaan.
Demonstrasi yang mengusung tuntutan “Bubarkan DPR RI” mungkin terlihat absurd secara konstitusi. Mustahil membubarkan lembaga legislatif dalam sistem demokrasi yang berpijak pada trias politika. Tetapi rakyat bukanlah buta. Mereka tahu itu. Justru di situlah letak pesan politiknya: tuntutan itu hanya percikan, semacam strategi membelokkan sorotan, agar istana tak merasa langsung diserang. Namun percikan bisa menyulut api. Sasaran sesungguhnya mudah beralih dari DPR yang dianggap boneka oligarki, ke istana yang menjadi pusat kendali kekuasaan.
Dan ketika tuntutan bergeser menjadi “Lengserkan Presiden”, permainan berubah total. Lawan-lawan politik Prabowo dari kalangan oligarki yang tergeser, partai-partai yang kecewa, hingga para koruptor yang terancam (bahkan bisa saja kepentingan politik luar negeri dimana Gerakan Presiden Prabowo dalam percaturan politik regional dan global cukup membuat Negara macam Maerika dan Autralia terlihat ketakutan) —akan dengan cepat menunggangi momentum. Chaos adalah lahan subur bagi konspirasi.
Karena itu, istana tak boleh terus menerus menutup telinga dengan retorika dan dalih keamanan. Setiap langkah represif hanya memperkuat narasi bahwa Prabowo adalah pewaris Orde Baru. Setiap kekerasan aparat hanya mengukuhkan trauma lama yang belum sembuh. Dan setiap korban baru hanya akan menjadi bahan bakar perlawanan.
Presiden punya dua pilihan: menegaskan keberpihakan kepada rakyat dengan langkah berani, atau membiarkan alarm ini berdentang semakin keras hingga akhirnya berubah menjadi lonceng perlawanan. Pecat Kapolri, munkin bisa menjadi langkah awal sebuah sinyal bahwa presiden masih punya keberanian moral untuk bertindak. Atau, jika mau mengambil jalan ekstrem, sebuah dekrit politik PEMBUBARAN DPR RI yang akan mengubah arah permainan mungkin bisa menjadi opsi. Tapi pilihan terakhir itu, sekali lagi, bukan tanpa risiko tapi kenapa tidak toh TNI sudsh dalam Kuasanya.
Sejarah mencatat, kekuasaan yang mengandalkan represi selalu berakhir di jalan buntu. Bayangan Soeharto dengan senyum penuh kuasa itu masih ada di benak rakyat, dan kini mereka melihat Prabowo di persimpangan jalan yang sama. Akankah ia mengulang sejarah? Atau memilih jalur lain yang lebih demokratis dan berpihak pada rakyat?
Alarm sudah berbunyi. Keras. Pertanyaannya adalah ” apakah presiden mendengarnya, atau memilih menutup telinga?. Kita tunggu saja etape Politik berikutnya……..semoga indoenesia tetap baik-baik saja.
Penulis Rausi Samorano.
Ketua Dewan Pembina LBH FORpKOT